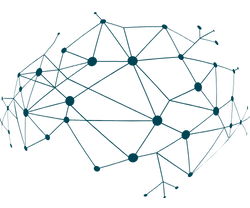Rendy Ananta Prasetya
Tidak ada satuan sosial yang sifatnya tunggal (berdiri sendiri) dalam kehidupan sosial (manusia), segala sesuatunya saling terkoneksi sebagai satu kesatuan sistem yang tidak bisa diipisah-pisahkan (Agusyanto, 2010, 2018; Chapra, 1996). Begitupun di dalam Politik, setiap entitas terhubung satu dengan yang lain, seperti Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 – 2029 dan jajaran Kabinet Menteri Merah Putih sebagai sekumpulan node (aktor) yang saling terhubung membentuk satu kesatuan jaringan yang kompleks, terdiri dari hubungan dyad (antar pasang) dan triad (antar tiga node/aktor).
Kompleksitas dinamika politik Indonesia tidak lepas dari tiga (3) node (aktor) pusat atau dalam jaringan dikenal sentrality; yakni Presiden RI Ke-8, ke-7 dan ke-5. Ketiga pusat ini saling mempengaruhi berbagai situasi dan arena politik seperti saat penentuan Calon Presiden 2024 – 2029 dan Penentuan Calon Gubernur di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan seterusnya). Kerjasama – Persaingan antar tiga (3) node ini menarik diamati khususnya ketika komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun kesepakatan politik, pemosisian strategis, tawar menawar sambil memperhatikan gerak dan tujuan (kepentingan) dari aktor lainnya. Ada saat – saat dimana kedua node (aktor) (1 dan 2) bersatu (bekerjasama) untuk melakukan persaingan dengan node (aktor) ke-3, ada kalanya node (aktor) ke-1 berpisah dengan node (aktor) ke-2 dan sepakat dengan pendapat node (aktor) ke-3. Namun node 2 dan 3 sementara ini sebisa mungkin tidak saling bekerjasama walau keduanya juga tidak bisa saling meniadakan. Di dalam jaringan sosial dinamika hubungan ini disebut dengan hubungan triadik / tiga – node. Pihak ke-3 dapat menjadi penyeimbang, ataupun musuh bersama, atau node (aktor) yang mampu mendamaikan keduanya, atau bisa juga menjadi pemecah antar keduanya.
Hubungan Triadik sebagai dasar arsitektur kompleksitas yang mempengaruhi dinamika politik Indonesia hari ini, dapat berkembang menjadi badai atau tsunami politik ketika konflik antar triadik sebagai poros sentral utama tidak dapat terhindarkan. Tetapi relatif dapat dihindari ketika kerjasama – persaingan itu terjadi di jaringan lapis kedua atau ketiga (cluster) jaringan. Hubungan antara poros sentral utama, dengan lapisan kedua dan ketiga merupakan jaringan dari sekumpulan jaringan yang lebih luas dan kompleks (network of Networks) (Wellman, 1973). Ibarat pertandingan sepakbola, masing-masing poros sentral utama jaringan ini memiliki ‘playmaker’ yang turut bertugas menyesuaikan gerak dan dinamika serta dialektika (interaksi antar aktor yang kontinyu) hingga membentuk suatu keteraturan dan ketetapan baru yang disepakati. Masing-masing poros sentral utama ini memiliki kehebatannya dan kepiawaian dalam menentukan arah pemerintahan Indonesia ke depan.
Politik tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan yang terdiri dari hubungan dyad/triad node yang spesifik pada konteks, dinamis dan berpotensi relatif tidak stabil. Mengapa demikian? Hubungan selalu bersifat asimetris karena selalu terdapat kontrol yang lebih besar atas perilaku orang lain (Knoke, 1994:1-3). Asimetris juga bisa berarti resiprokal karenanya kekuasaan pasti selalu membutuhkan konektivitas dan tidak tunggal (berdiri sendiri).
Pengaruh dan dominasi dalam politik terjadi melalui konektivitas antara aktor, seperti pertukaran informasi yang mengubah persepsi. Kekuasaan relasional ini mempengaruhi arena politik dengan pemberian tawaran atau pengendalian terhadap aktor lain, menciptakan keleluasaan atau ketidakleluasaan bagi mereka yang saling terhubung. Kekuasaan tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung antar node (aktor).
Seringkali dalam organisasi kelompok sosial tidak selalu memperhatikan perintah atasan (kepatuhan) bawahan karena konteks tidak selalu bergerak dalam kerangka hubungan formal organisasi ataupun bergantung pada aturan kelompok (Blau dan Scott, 1962:29) melainkan bersifat intersubjektif karena hubungan kekuasaan yang timbal balik mempengaruhi keleluasaan / ketidakleluasaan seseorang bertindak. Node dipengaruhi oleh hubungan sosial (relasional) yang dimilikinya.
Menariknya, dalam sebuah jaringan sosial tidak ada kesatuan yang bulat (utuh, tetap dan statis / tidak bergerak) melainkan selalu terdiri dari kesatuan – kesatuan sosial yang ada di dalamnya. Sehingga tidak ada yang tidak dapat dibelah, sebaliknya tidak ada yang tidak dapat dipersatukan. Seperti ungkapan lama, “tidak ada lawan dan kawan yang abadi” karena gerak dan keteraturan selalu dipengaruhi oleh gerak sebagai tanda kehidupan sosial (manusia) yang terhubung satu dengan yang lainnya.
Unit dasar kajian dari sistem politik yang kompleks saat ini terdiri dari keteraturan antar individu dan posisi sentral yang ditempati serta hubungan sosial yang membentuknya (bisa dua atau lebih node yang saling mempengaruhi). Jika secara konvensional Tindakan dipahami sebagai hasil dari kumpulan, hak, tugas, kewajiban dan harapan yang diartikulasikan oleh perilaku orang – orang yang mengambil posisi tersebut dalam sistem sosial (Baca Linton, 1936:113; Nadel, 1957:20-44, 102). Maka sekarang, memahami cara pandang sistem politik yang kompleks, tidak cukup pada status, hak dan kewajiban tetapi juga harus relasional.
Analisis Jaringan Sosial (Social Network Analysis) sebagai analisis sekumpulan node (aktor) yang tersatukan oleh hubungan – hubungan ikatan / garis (edge) merupakan alternatif cara pandang untuk mengungkap bentuk dan proses mendasar dari perilaku politik saat ini. Struktur hubungan antar jaringan (dan antar aktor) membatasi serta memberikan keleluasaan / ketidakleluasaan bertindak serta menimbulkan konsekuensi perilaku, persepsi bagi unit individu politik dalam sebuah sistem sosial (Knoke dan Kuklinski, 1982:13). Pakar lain menekankan pentingnya pola hubungan dari para node (aktor) yang terlibat khususnya pada muatan sosialnya (social content) yang membentuk sikap dan perilakunya (Baca lebih jauh dalam Agusyanto, 2007; 2010; 2018; dan Mitchell, 1969).
Muatan sosial juga dapat berarti distribusi kekuasaan antar node (aktor) dalam jaringan dari sekumpulan jaringan dan kemampuannya untuk menghasilkan dampak signifikan (atau yang diinginkan) terhadap sikap atau perilaku aktor lainnya seperti transmisi informasi / sumber daya berharga bagi suatu jaringan. Aliran muatan sosial dengan hubungan pertukaran antar node (aktor) dalam sistem jaringan (Knoke dan Burt, 1983:198) transmisi biasanya melibatkan beberapa posisi – posisi sentral dan hubungan timbal baliknya (resiprokal) seperti barang, jasa, pengaruh, informasi, dan sebagainya (Freeman, 1977, 1979). Dalam pertukaran politik seperti misalnya jaringan patron-klien, penghargaan kinerja (atau pengabdian), tukar menukar kewenangan atau sumber daya, berbagai fasilitas (muatan sosial) mengalir antar node (aktor) yang memberikan atau menghidupi sebuah jaringan sosial secara signifikan (Tichy dan Fombrun, 1979; Bacharach dan Lawler, 1980:203-223).
Ada cerita dari struktur dinamika politik 2024 hari ini yang dipengaruhi oleh keteraturan jaringan hubungan sosial. Pertama, bahwa ketiga poros sentral utama di atas turut memberikan warna pada politik Indonesia hari ini dimana keberimbangan dari ketiga poros sentral utama yang saling menunjukkan orkestrasi kekuasaannya, saling menempatkan diri, menyeimbangkan posisi akibat representasi hubungan triadik yang terus berdialektika. Kedua, hubungan sosial dari ketiga poros 1,2,3 diatas tersebar di berbagai jaringan – jaringan sosial yang ada hari ini baik di lapisan pertama atapun kedua. Ketiga, tidak melulu mengenai bentuk pemerintahan yang akomodatif / representasi tetapi juga bagaimana menempatkan node – node (aktor) tertentu untuk menjaga integritas, fungsi, keselarasan dan harmonisasi jaringan – jaringan yang ada.
Ada bidang – bidang yang diisi oleh satu jaringan sosial kepentingan yang sama, ada juga bidang – bidang yang diisi oleh beberapa jaringan yang berbeda – beda. Jika jaringan tersebut diisi oleh jaringan kepentingan yang sama, maka tujuannya adalah untuk berjalan beriringan, mempercepat program dan melaksanakan suatu tujuan tertentu, sedangkan jika bidang tersebut berasal dari beberapa jaringan sosial yang berbeda – beda (atau bahkan bermusuhan), bisa juga tujuannya adalah untuk saling menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan secara berjamaah, misalnya pada Kementerian – Kementerian (dan Kementerian Koordinator) yang tadinya satu kemudian dipecah.
Adapun beberapa bidang yang disisipkan untuk tujuan / kepentingan tertentu misalnya oleh pengusaha besar untuk menjaga sumber daya ‘milik’nya agar tidak terganggu. Sumber daya yang dimiliki / dipelihara oleh sebuah jaringan sosial yang sifatnya lintas batas begitu besar dengan nilai yang fantastis. Ada juga yang merupakan titipan dari adik / istri dari poros – poros sentral utama kekuasaan. Atau bahkan ada node (aktor) yang perannya adalah sebagai jaminan atau kuda troya yang sewaktu – waktu dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti menjadi duri dalam daging yang terus hidup dalam sebuah kesatuan sosial (bisa partai atau kelompok sosial lainnya). Aktor ini bisa menjadi titik pembelah / pemersatu dari kesatuan sosial (tergantung konteks sosialnya). Aktor ini juga menitipkan sejumlah nama yang berhasil dipasang / disetujui untuk dipasang sebagai sebuah ‘jaminan’.
Selain penyusunan Menteri, Badan Usaha Milik Negara dan ‘ketua – ketua kelas’ yang akan menguasai sumber daya juga akan dirombak pasang. Hal ini akan tergantung pada posisi tawar dari masing – masing jaringan (dan aktor sentral) di dalamnya, khususnya mereka yang mampu beroperasi lintas batas dan menguasai bidang – bidang tertentu. Jika sumber daya tersebut mensyaratkan penguasaan teknologi yang tinggi, tentu akan sulit dibandingkan dengan bidang dari sumber daya yang tidak mensyaratkan teknologi yang tinggi, tetapi misalnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka tentunya aktor – aktor yang bermain di poin pertama ini akan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan poin yang kedua. Hal ini penting mengingat bagaimana sumber daya tersebut secara signifikan mempengaruhi kelangsungan organisasi jaringan.
Ketika pemerintahan sudah berjalan, node (aktor) ini bisa saja nanti terlibat friksi atau terpecah ketika kepentingan tadi menjadi berbeda (konteksnya) menjadi Kerjasama – Persaingan atas sumber daya sehingga suka atau tidak suka terpaksa harus berhadap – hadapan dan memperjuangkan kepentingannya. Itulah mengapa berulang kali RI ke-8 menekankan pentingnya persatuan, pentingnya kesetiaan pada bangsa dan negara (bukan pada kepentingan golongan / jaringan).
Potensi konflik antar jaringan yang terjadi misalnya pimpinan pertama dan kedua (sebagai representasi poros sentral yang utama), para pendukungnya, antar kementerian (dan juga koordinator kementerian), legislatif – eksekutif, legislatif – legislatif, antar pengusaha (jaringan pengusaha) dan lain sebagainya. Contoh paling nyata ketika baru saja pemilihan Presiden selesai Kamar Dagang Industri (Kadin) langsung bergejolak.
Keempat, Presiden RI ke-8 juga tidak hanya mengandalkan hubungan Presiden – Menteri, tetapi juga ada Penasehat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden, struktur ini dilakukan untuk mengimbangi arus informasi yang hanya satu arah, tetapi bisa multi-direction. Hal ini bisa mengurangi dampak dari perang jaringan yang terjadi. Kelima, penguatan institusi tertentu sebagai aparat penegak hukum bisa jadi akan terus menguat dan pertarungan kewenangan bisa saja juga berpindah, atau yang tadinya berada di kementerian / badan bisa dipindah ke (misalnya) aparat penegak hukum tertentu.
Untuk memitigasi potensi konflik dan perang jaringan yang terjadi ada baiknya kesatuan dan keserempakan gerak menjadi penting untuk pemerintahan Indonesia ke depan. Agar kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan diatas kepentingan individu – individu (jaringan) yang saling terhubung dan rekonsiliasi. Kedua, pentingnya mengidentifikasi relasi – relasi yang sifatnya lintas batas khususnya bagi mereka (broker – broker) yang mampu beroperasi lintas batas dan memiliki jaringan yang luas dalam pertemanan, jaringan kepentingan dan lain sebagainya.
Terakhir, keteraturan jaringan menjadi relevan untuk digunakan dalam membaca gerak dan keteraturan – keteraturan yang dibuat dalam konteks politik khususnya dalam memahami kompleksitas hubungan sosial, gerak, struktur dibalik fenomena politik Indonesia saat ini. Mari kita harapkan bahwa ‘perwira-perwira’ bangsa saat ini dapat bekerja dengan baik memperjuangkan kepentingan nasional kita dalam rangka menuju tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur tidak hanya untuk kepentingan tertentu tetapi juga segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Salam,
Peneliti, Asosiasi Peneliti Jaringan Sosial Indonesia (APJARSI)
Disclaimer: Opinions expressed here are solely my own and do not express the views or opinions of the organization
Daftar Pustaka
Agusyanto, Ruddy. 2018. Berpikir Jaringan. Pusat Analisis Jaringan Sosial (PAJS). Jakarta, Indonesia.
—- 2010, Jaringan Sosial dalam Organisasi, Jakarta, Rajawali Press
—- 2021, Gerak dan Keteraturan di Era Digital, Pusat Analisis Jaringan Sosial (PAJS), Jakarta
Blau, P.M., & Scott, W.R. (1962). Formal organizations: a comparative approach. Chandler.
Chapra, Fritjof. 1996. The Web of Life: a new scientific understanding of living systems. Anchor Books, New York, 1996.
J. Clyde Mitchell (ed.). 1969. Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal Relationships in Central African Town. Manchester University Press for the Institute for Social Research, University of Zambia.
Knoke D., Burt R. S. (1983). Prominence. In Applied network analysis (pp. 195–222). Sage.
Knoke, David. 1994. Political Networks: The Structural Perspective. Cambridge University Press ELT.
Linton C. Freeman. 1979. Centrality in Social Networks Conceptual Clarification. Social Networks Vol. 1 Issue 3, 1978-1979, pg215-239. Lehigh University, Price Hall, USA. https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7
S. B. Bacharach and E. J. Lawler, “Power and politics in organizations,” San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1980.
Tichy, N., Tushman, M., & Fombrun, C. (1979). Social Network Analysis for Organizations. Academy of Management Review, 4, 507-519. Wellman, Barry (1973). “The Network City”. Sociological Inquiry. 43 (3–4): 57–88. doi:10.1111/j.1475-682X.1973.tb00003.x.