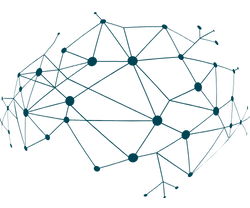79 tahun berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 1945, dan 21 tahun lagi menuju 100 tahun berdirinya negara Indonesia penting untuk merefleksikan Kembali apa arti menjadi manusia Indonesia. Sebagaimana pernah ditulis oleh Mochtar Lubis (1977) tentang konsepsi negatif Manusia Indonesia dan juga pernah ditulis oleh seorang budayawan Radhar Panca Dahana (2001) “Menjadi Manusia Indonesia” yang banyak melakukan kritik terhadap pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.
Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul pertanyaan mendasar di benak penulis mengenai “Seperti Apa rasanya menjadi Manusia Indonesia?” atau bagaimana manusia Indonesia sejatinya? Sedangkan sedari lahir, kita tidak serta merta langsung menjadi orang Indonesia tetapi orang Jawa, orang Bugis, orang Minang, Sunda, Kalimantan dan lain sebagainya. Sebagaimana pernah ditulis oleh Parsudi Suparlan, Guru Besar Antropologi, bahwa sukubangsa (ethnic group) keanggotaannya didapat dari lahir atau yang disebut dengan askriptif. Karena bersifat askriptif, suku mengandung prinsip primordialisme (yang mendasar, utama dan paling pertama) didapatkan oleh manusia Indonesia. Hal ini kemudian memperkuat etnosentrisme, yang menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku yang lain Suparlan (2005) ini menjadi ancaman potensi disintegrasi bangsa Indonesia yang nyata.
Prof. Achmad Fedyani Saifuddin (2005) juga mengungkapkan pentingnya proses menjadinya sebuah bangsa atau manusia Indonesia yang tidak lepas dari satuan kehidupan politik, satuan kehidupan bangsa dan satuan kehidupan kebudayaan yang berkelindan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mengutip Benedict Anderson (1993), bangsa sebagai komunitas yang dibangun secara sosial (socially-constructed), dibayangkan atau diimajinasikan oleh orang – orang yang menganggap dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok (1991:6-7). Bangsa mewujud dikarenakan kehendak Bersatu sebagaimana Renan ataupun persatuan komunitas yang senasib (community of fate) kata Otto Bauer dalam Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie” (Pertanyaan tentang Kebangsaan dan Sosial-Demokrasi) (Bdk. Bauer, 1907; Bauer, 2000) yang dikutip oleh Soekarno dalam Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945 mengenai syarat berdirinya sebuah bangsa. Jika demikian maka, bangsa merupakan kumpulan konsep, pengetahuan yang dikonstruksikan secara sosial seperti dalam tulisan Berger dan Luckman (1966) yang berjudul The Social Construction of Reality mengandung artiKe-Indonesiaan yang tidak serta merta begitu saja ada.
Olimpiade tahun 2024 merupakan satu diantara banyak ajang lain dimana kita bisa merasa satu Indonesia, begitupun dengan berbagai acara perlombaan 17 agustusan yang selalu kita lakukan setiap tahunnya sebagai satuan politik dan sosial budaya. Begitu juga saat Olimpiade tahun 1992 dimana Susi Susanti dan Alan Budikusuma meraih medali emas. Kita bisa merasa sebagai orang Indonesia apapun suku dan etnisnya.
Kalau para pendiri bangsa di Indonesia selalu bicara mengenai politik persatuan atau persatuan nasional, maka ancaman terbesar terhadap kesatuan bangsa adalah disintegrasi melalui politik kesukuan (politik identitas) yang mengutamakan politik pembelahan dibanding politik persatuan.
Politik pembelahan berusia setua peradaban manusia dan terjadi di berbagai belahan dunia manapun yang mengancam sebuah negara-bangsa. Di Yugoslavia misalnya perseturuan antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia dan memiliki persinggungan antara Muslim, Ortodoks Timur dan Katolik, Suni dan Syiah di Irak, Pashtun di Afghanistan antara Suni – Muslim, Tajik, Uzbek dan Hazara, Pakistan – India, bahkan di negara maju seperti Inggris (Skotlandia, Wales, Irlandia) dan lain sebagainya (Chua, 2020). Di Indonesia sendiri konflik suku juga pernah terjadi antara lain Poso, Sulawesi Tengah, Sampit – Madura di Kalimantan, Ambon, Lampung yang berdampak secara luas dan menimbulkan korban jiwa. Hal ini juga termasuk menyebabkan stereotipe yang berkembang antar kelompok / kesatuan sosial masyarakat, egoism antar golongan sosial, egoism kedaerahan – pusat, berkurangnya tenggang rasa, tolong menolong, gotong royong dan nilai – nilai Pancasila sebagaimana ditulis dalam Strategi Pertahanan Negara (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 tahun 2014).
Menjadi manusia di masyarakat modern saat ini dengan berbagai interkonektivitas yang tinggi akibat perkembangan teknologi informasi komunikasi membuat dinamika, kompleksitas dan perubahan sosial semakin tinggi, sebagaimana ditulis oleh Castells (2009) dalam masyarakat jaringan (network society) yang terhubung antara dimensi online – offline.
Konteks sosial dapat berganti relatif cepat saat ini artinya membangun perpecahan / pembelahan dengan politik persatuan sebenarnya sama prosesnya. Merancang pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaannya sebagai proyek abadi nasionalisme Indonesia agar terus menjadi (sebagai proses) manusia Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia in the making adalah proyek yang tiada berakhir untuk Indonesia dalam menentukan arah nasionalisme bangsa.
Merajut infrastruktur sosial budaya tidak kalah pentingnya dengan pembangunan fisik seperti Jembatan, Gedung dan lain sebagainya. Dalam arti sebagai manusia maka Kerjasama – persaingan dalam kehidupan sosial bersifat kodrati karena Ia merupakan mekanisme dan fungsi – fungsi pemenuhan kebutuhan hidup seseorang yang dikelilingi dengan berbagai bahan baku, ketersediaan dari alam lingkungan, mengolah berbagai energi, pangan dan lain sebagainya. Gotong royong yang menguatkan nilai – nilai persatuan penting untuk selalu dilestarikan dan dijadikan sebagai sebuah platform komunal yang dapat mengakselerasi pembangunan manusia dan kebudayaannya. Tidak lupa pengawasan terhadap daya saing, dan daya adaptasi kesatuan sosial masyarakat yang penting untuk menghindari rasa ketidakadilan yang dapat memicu atau menyuburkan benih – benih potensi konflik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini penting karena secara mendasar, alam lingkungan (dan energi) yang ada di setiap kewilayahan Indonesia, dari sabang sampai Merauke, Rote ke Miangas, selalu memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda – beda dan setiap manusianya pun juga berbeda – membangun setiap sistem keyakinan, organisasi sosial, politik, dan lainnya dalam satu wadah bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
Mengutip Soekarno (1956), “Masing – masing pulau beranggapan bahwa dirinja adalah suatu kesatuan jang mutlak dan tidak ada satu suku jang rela berkorban untuk seluruh Indonesia. Saja tidak mengandjurkan supaja orang sunda mentjintai daerah pasundan, atau supaja orang djawa mentjintai daerah Djawa, atau Orang Bali mentjintai daerah Bali, atau supaja orang Minangkabau mentjintai daerah Minangkabau, atau orang Atjeh menctjintai daerah Atjeh. Tjintailah, majukanlah daerahmu masing – masing tapi djanganlah lupa bahwa daerahmu masing – masing adalah bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari satu tubuh jaitu tanah air, bangsa, Bahasa Indonesia” (Soekarno, 10 November 1956, Waktu membuka Sidang Konstituante, Kementerian Penerangan RI).
Dalam menjaga interaksi dan hubungan antar kesatuan sosial yang ada di sekitar manusia Indonesia, baik sesama manusia maupun hubungan manusia dengan yang bukan-manusia (hewan, tumbuhan, gunung, sungai dan lainnya) sebagai satu kesatuan pandangan holistik yang tidak bisa dipisahkan. Pandangan “Tat Tvam Asi yang artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku” dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan, keselarasan hubungan antar manusia (Soekarno, 1958) karena kondisi kodrati alam dan manusia Indonesia yang beranekaragam dan setiap individu / manusia Indonesia yang selalu bersifat heterogen. Dominan yang berlebihan sampai berkembang menjadi nafsu untuk menguasai / mendominasi tidaklah dibenarkan ibarat kolonialisme dan imperialism (Indonesia Menggugat, 1930).
Proses menjadi manusia Indonesia maka adalah tentang mengatur hubungan antar manusia agar saling hidup selaras, harmoni antar sesamanya dengan berbagai keanekaragaman sosial yang ada dan pemenuhan – pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hubungan Antar manusia adalah saling mengatur Kerjasama – Persaingan di dalam kerangka gotong royong yang bisa mengakselerasi pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia untuk memperkuat rasa keIndonesiaan yang ada. Perbedaan tidaklah harus dihilangkan (atau diseragamkan) karena segala hewan dan tumbuhan juga beranekaragam. Melainkan harus diselaraskan di setiap waktu dan jamannya, menghubungkan berbagai kesatuan sosial (manusia Indonesia) beserta dengan berbagai muatan sosialnya untuk menuju pada satu tujuan yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
MERDEKA!!
Daftar Pustaka
Achmad Fedyani Saifuddin, 2006. Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma. Jakarta. Kencana.
Anderson, Benedict R. O’G. (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism (Revised and extended. ed.). London: Verso. pp. 6–7. ISBN 978-0-86091-546-1.
Amy Chua, 2020. Political Tribes: Group instinct and the fate of nations. New York. Penguin Press.
Berger, P.L. and Luckmann, T. (1966) The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Doubleday & Company, New York.
Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford: Oxford University Press.
Parsudi Suparlan, 2007. Hubungan Antar Sukubangsa. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Soekarno, 1958. Pancasila membuktikan dapat Mempersatukan Bangsa Indonesia. Pidato Presiden Soekarno pada Peringatan Lahirnya Pancasila di Istana Negara tanggal 5 Juni 1958.
Soekarno. (1930). Indonesia Menggugat. Departemen Penerangan RI.
Soekarno. (1964). Di Bawah Bendera Revolusi. Departemen Penerangan RI.
Peraturan Perundang – Undangan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 tahun 2010